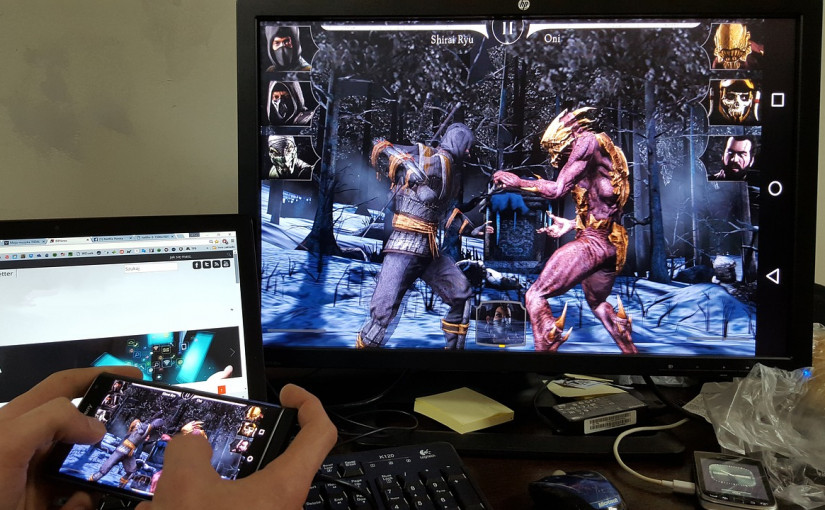Seperti yang terungkap dalam tulisan sebelumnya, bisnis game cenderung dekat dengan konsep gambling. Ada faktor X yang menjadi penentu sukses atau tidaknya suatu produk. Modelnya sama seperti saat membuat film dan lagu. Agar semakin paham dengan industri game, coba simak prinsip dasar bagaimana perusahaan game melakukan monetisasi.
Ambil contoh terdekat mobile game kekinian seperti Mobile Legends yang sedang digandrungi Gamal dan orang Indonesia lainnya. Game ini memanfaatkan in-app purchase untuk monetisasinya. Caranya dengan membuat item dan fitur dalam setiap hero yang disematkan. Sistem pembayarannya menggunakan diamond atau poin yang dikumpulkan setiap kali bermain.
Harganya bervariasi, untuk memperoleh 250 diamond perlu merogoh kocek Rp75 ribu, 500 diamond Rp149 ribu, hingga yang termahal 5 ribu diamond senilai Rp1,49 juta. Lewat cara ini, perusahaan game mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan porsi yang sudah disetujui dengan Android/iOS. Kisarannya untuk perusahaan game sebesar 70% dan untuk Google 30% bila memakai platform Android.
Ada cara lain mendapatkan keuntungan bila memasarkan produk lewat mobile, yakni iklan. Salah satu platform yang menyediakan layanan ini adalah Admob dari Google. Rumus kasar yang bisa diterima perusahaan lewat iklan adalah Daily Active User (DAU) x Session x Harga Iklan / 1.000.
DAU adalah berapa banyak orang yang memainkan/membuka aplikasi dalam sehari. Session itu berapa kali pemain membuka aplikasi dalam sehari. Sedangkan harga iklan adalah biaya yang dibayarkan dari aktivitas iklan di aplikasi.
Cara monetisasi terakhir dari mobile game adalah membuat game berbayar. Sekali membayar, pengguna dapat mengunduh aplikasi secara eksklusif.
Sumber pendapatan lain bagi perusahaan game adalah memproduksi game premium untuk PC dan konsol. Untuk game PC bisa dijual lewat platform Steam. Sedangkan konsol bisa dijual secara digital atau fisik lewat prinsipal masing-masing, yakni Nintendo, Xbox, dan PlayStation.
Cara monetisasi di atas hanya berlaku ketika perusahaan menjual produk game buatan mereka sendiri, atau lebih mudah disebut dengan business to consumer (B2C). Perusahaan sebenarnya juga bisa mengambil proyek lepas untuk klien (B2B), ini disebut advergame.
Terakhir, perusahaan juga bisa menjual merchandise karakter game yang mereka buat. Cara ini bisa dilakukan jika karakter game sudah kuat dan berbekas di benak pengguna. Ambil contoh termudah adalah karakter Angry Birds. Merchandise karakter ini beragam mulai dari t-shirt, gelas, mug, gantungan kunci, topi, hingga pakaian untuk pria maupun wanita.
Meski industri game kurang mendapat bantuan pendanaan dari pemodal lokal, bagi orang-orang sudah sedari awal punya passion kuat dengan bisnis ini, halangan apapun akan ditebas, termasuk soal pemodalan.
Dari tiga perusahaan game yang ditemui penulis, ketiganya memang pada akhirnya mendapat investasi dari modal ventura supaya bisa melakukan ekspansi bisnis. Meskipun demikian, semua pendiri punya pengalaman sama ketika mengawali bisnisnya. Yaitu, merogoh kocek sendiri saat awal bisnis berdiri.
Para pendiri ini enggan memberi tahu penulis tentang detail pendapatan yang mereka peroleh dengan berbagai alasan, namun mereka bersedia menceritakan perjalanan merintis bisnis hingga seperti sekarang.
Toge Productions

Toge Productions adalah perusahaan game indie yang didirikan Kris Antoni bersama seorang temannya pada 2009. Keduanya tertarik terjun ke industri ini karena sempat mengambil waktu senggang di luar jam kantor ikut kompetisi game.
Sejak itu, mereka sadar bahwa industri game ini ada pasarnya. Kebetulan jenis game yang tenar pada saat itu adalah game flash. Model bisnisnya, kreator menawarkan produknya ke situs marketplace khusus game Flash untuk dilelang (bidding) dan masuk sebagai koleksi konten.
Ketika pemilik marketplace tertarik, artinya game tersebut laku terjual dengan harga bidding. Konsep setiap marketplace berbeda-beda, ada yang diperuntukkan untuk konten eksklusif, ada yang tidak. Nama-namanya seperti Flash Game License dan Kongregate.
Game Flash pertama yang dibuat Toge adalah Days 2 Die di 2009, terjual dengan harga US$3 ribu (kurs dollar Rp10 ribu) dan proses pengerjaan selama tiga bulan. Perolehan ini tentu membawa untung bagi mereka berdua, sebab modal awal yang dialokasikan untuk Days 2 Die sekitar Rp20 juta. Itu berasal dari masing-masing sisa tabungan.
Kemudian, Toge mulai menyeriusi bisnis game dengan rajin membuat game berbasis Flash. Seluruh hasil penjualannya, kembali diputar untuk produksi game baru yang lebih ambisius. Untungnya, game berikutnya dari Toge memiliki nilai jual lebih besar, sehingga menghasilkan profit sekitar Rp1 juta-Rp2juta. Di tahun kedua, Toge sudah bisa merekrut orang baru.
“Modalnya hanya dari tabungan untuk hidup dan laptop masing-masing yang sudah punya. Kita selalu usaha untuk selalu irit, bahkan pernah makan indomie saja selama tiga bulan,” terang Kris.
Penjualan utama Toge adalah produk B2C, membuat game premium khusus untuk PC dan konsol. Sasaran pengguna Toge adalah internasional, bukan lokal. Dengan cara itu, menurut Kris, justru perusahaan bisa lebih sustain karena bisnis game premium lebih jelas dan tidak serumit mobile game.
Toge sempat mengambil bisnis advergame untuk B2B. Namun terpaksa dihentikan karena penghasilan yang didapat kurang sesuai dengan jerih payah.
Agar Toge tetap bertahan, perusahaan berusaha untuk menekan beban ongkos operasional dengan meminimalkan jumlah karyawan. Makanya kualitas karyawan yang dicari Toge adalah multi skill. Mereka bisa bantu untuk musik, desain, art, dan lainnya.
“Kita selalu berusaha setiap merekrut orang harus kalkulasi gajinya, apakah make sense dengan budget yang ada. Apakah bisa di-cover dengan tenaga yang kita punya sekarang. Kalau ternyata [budget] enggak cukup, ya lakukan sendiri. Jika memang benar-benar butuh baru hire orang.”
Dengan memutar keuntungan saat merintis Toge, Kris mengaku tidak pernah memiliki rencana untuk mengambil pinjaman dari pihak manapun. Entah itu bank ataupun ke orang tua sendiri. Sebab, hal ini sama saja menambah risiko.
“Jujur saja, kami rada anti dengan minjem ke bank karena itu nambah risiko. Kami lebih suka manage dari apa yang kita punya. Jangan sampai ada kondisi terpaksa pinjam. Syukurnya itu belum pernah terjadi di Toge.”
Kris pun menggambarkan struktur keuangan yang dimiliki Toge dengan proses produksi game. Setiap Toge ingin membuat proyek baru, pihaknya membuat estimasi berapa lama proses pembuatannya. Misal estimasi yang dibuat adalah 6 bulan, maka Toge harus menyiapkan gaji karyawan dan biaya operasional kantor sesuai rentang waktu tersebut.
Karena ada faktor X, kemungkinan proyek bisa molor maka perlu ada buffer. Toge mengalikan estimasi awal hingga dua kali lipat, sehingga dapat estimasi akhir satu tahun proyek game harus selesai. Selama setahun, sedari awal Toge sudah memastikan budget-nya telah siap.
“Kita selalu coba untuk tetap slim dan small. Semakin banyak orang belum tentu buat proyek cepat selesai. Malah bisa buat biaya makin besar. Banyak yang enggak sadar, di industri kreatif itu mindset-nya jangan kayak buat pabrik. Bukan berarti ada dua orang bisa buat puisi lebih cepat.”
Proses pengerjaan game, dimulai dari pemilihan tema. Toge selalu berusaha untuk menghindari tren dan mengambil dari sisi lain. Toge jarang sekali melakukan riset pasar untuk mencari tahu kemauan pasar seperti apa.
Ambil contoh untuk game Infectonator. Membawa karakter zombie lantaran alasan pribadi Kris yang penyuka makhluk tersebut. Permainan ini mengandaikan diri Anda sendiri sebagai penyebar wabah untuk menyerang seluruh manusia. Tujuan akhirnya semua manusia musnah dan menjadi zombie.
Cara memainkannya, Anda hanya cukup tap layar smartphone dan melakukan beberapa upgrade untuk pasukan zombie. Game ini pertama kali rilis sebagai game Flash, lalu di-port ke mobile game pada 2012. Untuk proses pembuatannya sendiri dimulai pada 2011.
“Infectonator itu game paling populer di Toge. Itu game yang benar-benar di luar tren dan genre manapun. Kebetulan iseng mau buat game yang simpel, gak perlu mikir. Lalu dapat inspirasi saat main salah satu game flash, cara mainnya reaksi berantai, tapi itu bom. Itu lucu sih, akhirnya kita brainstorming untuk mengembangkan lebih lanjut.”
Saat membuat Infectonator, belum ada tambahan karyawan selain Kris dan Jonathan. Awalnya membuat minimum viable product (MVP) berisi inti dasar game sebelum ditambah fitur lainnya sehingga menjadi versi penuh. Berangkat dari MVP, Toge ingin melihat respon pasar apakah orang suka dan bagaimana masukannya.
Setelah berhasil membuktikan banyak pengguna yang memberi masukan, Toge mulai menambah fitur-fitur tambahan yang terbagi menjadi beberapa milestone. Setiap milestone membutuhkan waktu pengerjaan sekitar 2-3 bulan.

Dengan pembagian milestone ini, Toge mau membuktikan apakah fitur yang satu per satu ditambahkan ini bisa diterima pengguna atau tidak. Bila tidak, Toge bisa mengatasi risikonya sedini mungkin. Intinya, proses pengerjaan game tidak boleh melebihi budget yang sudah ditentukan sejak awal proyek dimulai.
Untungnya karena dipecah-pecah menjadi milestone, Toge punya kesempatan untuk men-spin off menjadi game tersendiri. “Berkat ada milestone, menjadikan rate of failure kami tidak tinggi. Dari semua proyek, yang fail atau enggak kelar sekitar 30% dari total produk. Untungnya begitu.”
Kris mengklaim Infectonator masih menjadi produk game terbesar yang memberikan pendapatan ke perusahaan, meski sudah lama dirilis. Meski tidak disebutkan pendapatan terkini dari game tersebut, namun dia menggambarkan pada tahun pertama dirilis pendapatan kotornya mencapai Rp2 miliar. Angka tersebut berasal dari in-app purchase dan pembelian aplikasi di iOS. Adapun jumlah unduhan Infectonator itu sendiri di Google Play telah mencapai 5 juta kali.
“Dengan perbanyak produk berkualitas, kita ingin produk punya tale yang panjang dan terus make money, seperti Infectonator itu. Satu game bisa terus make money sampai lima tahun kemudian, lalu diakumulasi dengan game lainnya itu akan cukup menghidupi Toge. Dari segi effort, maintenance-nya tidak tinggi karena kami perlakukan game sebagai produk, bukan servis.”
Untuk menambah sumber pendapatan, kini Toge menambah divisi bisnis baru yakni publisher game mulai pertengahan tahun ini pasca DNC masuk sebagai investor. Ada tujuh game dari perusahaan game lokal yang menjadi mitra Toge, beberapa di antaranya Ultra Space Battle Brawl (Mojiken Studio), My Lovely Daughter (GameChanger Studio), Hellbreaker (Tahoe Games), dan MagiCat (Kucing Rembes).
Untuk model bisnis sebagai Toge Publisher, perusahaan memberikan bantuan pendanaan sebesar 50% dari total budget perusahaan game. Kemudian Toge akan membantu pemasaran dan konsultasi. Pembagian komisi antara Toge dengan perusahaan game adalah 30-70 atau 50-50 tergantung kesepakatan.
Secara total, Toge telah memproduksi sekitar 30 game. 20 di antaranya adalah game Flash, dan sisanya adalah game premium untuk PC dan konsol. Sebagian game juga tersedia versi mobile yang dipublikasi lewat pihak ketiga. Mobile game yang hadir dalam versi aplikasi di antaranya Infectonator Hot Chase dan Infectonator.
Arsanesia
Beda perusahaan beda strategi. Perusahaan game asal Bandung Arsanesia sempat menawarkan bisnis servis B2B untuk mendapatkan arus kas. Arsanesia didirikan oleh Adam Ardisasmita beserta tiga kawannya pada April 2011.

Arsanesia mulanya berdiri karena kampus Adam, Institut Teknologi Bandung (ITB), menggelar kompetisi bekerja sama dengan Nokia. Ketika itu perlombaan membuat mobile game dengan sistem operasi Symbian di 2010. Adam pun tertarik. Sepuluh ide terbaik mendapat hadiah sebesar US$4 ribu dan tim Adam terpilih jadi salah satu pemenang.
Aplikasi yang dia buat adalah Gamelan Player, game simulator alat musik tradisional Gamelan asal Sunda dikemas dalam bentuk digital untuk ponsel Nokia. Aplikasi tersebut kemudian dibawa ke Singapura untuk menjadi showcase. Responnya terlihat dari awal peluncuran. Sekitar 80% unduhan berasal dari luar negeri dengan total perolehan 200 ribu unduhan.
Setahun berikutnya, Arsanesia kembali melanjutkan kolaborasi dengan Nokia dengan meluncurkan mobile game Temple Rush: Prambanan. Temanya masih membawa budaya lokal, kebetulan pada saat itu marak terjadinya klaim budaya Indonesia oleh Malaysia. Adam dan tim pun mulai berkomitmen untuk menyeriusi dunia kewirausahaan di industri game dengan membentuk badan hukum di 2013.
“Saya termasuk salah satu kelompok yang mendapat stimulus awal dari Nokia untuk terjun di dunia game. Mereka kasih stimulus dengan mengeluarkan jutaan Euro untuk developer game lokal [meng]-upgrade pengetahuan, dapat bantuan dana, dan exposure-nya,” kata Adam.
Menurut Adam, apa yang dilakukan dari Nokia pada waktu itu merupakan stimulus terbesar yang membuat perusahaan game lokal tetap bisa bertahan hingga kini. Setelah Nokia diberitakan diakuisisi Microsoft, banyak studio game berguguran karena mereka tidak mempersiapkan rencana bisnis yang matang. Seolah-olah, dukungan yang tadinya melimpah tiba-tiba hilang begitu saja.
Syukurnya Arsanesia sudah mempersiapkan diri dengan terjun sebagai perusahaan yang menyediakan jasa servis untuk korporat (B2B), semenjak rutin berkolaborasi dengan Nokia. Dengan bekal pengalaman tersebut, Arsanesia menawarkan servis advergame ke korporat sejak 2011 hingga 2014 untuk tetap menghidupi perusahaan.
Saat fokus ke B2B, Adam sempat mengajukan kredit ke bank. Proposalnya hampir disetujui bank. Arsanesia menggunakan invoice dari klien sebagai agunan. Namun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengambil. Pertimbangannya karena kebutuhan dana selain diarahkan untuk menyelesaikan permintaan klien juga ada keinginan pengembangan produk B2C.
“Kami percaya masih perlu tambahan ilmu dan dari B2B itu salah satu solusinya. Jadi win win, kita bisa belajar sekaligus dibayar.”
Biaya yang digunakan untuk membuat Roly Poly sebesar Rp250 juta dengan rentang waktu pembuatan selama satu tahun. Seluruh anggaran tersebut habis untuk membayar gaji karyawan sekitar 8 orang terdiri atas animator, artist, programmer, game designer, magang, serta memakai jasa sound effect game dari pihak ketiga.
Sedangkan untuk ongkos pemasaran lebih banyak memakai strategi organik dengan memanfaatkan media sosial dan cross promotion dengan pengembang game lainnya. Tak hanya itu, strategi pemasaran Arsanesia lebih diarahkan meningkatkan visibilitas produk dalam Google Play, misalnya muncul dalam Features dan Editors Choice.
Cara tersebut dinilai lebih efektif, murah, dan Arsanesia bisa mendapatkan user yang lebih berkualitas karena potensi untuk meng-uninstall (churn rate) rendah.
“Dari hasil perolehan di B2B, kami tabung profit sedikit demi sedikit untuk modal mengembangkan produk B2C. Ternyata Roly Poly Penguin enggak hit, setelah sekian lama kami tidak buat produk. Akhirnya agar perusahaan tetap berjalan, kami terpaksa jalanin B2B lagi.”
Kemudian di 2016, Arsanesia bertemu dengan mitra yang tertarik dengan mobile game dan peduli dengan edukasi anak. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membentuk unit usaha baru, Arsa Kids. Ada tujuh produk dari Arsa Kids yang sudah dirilis, seperti Pippo Belajar Alfabet, Pippo Belajar Bentuk, Pippo Belajar Rasi Bintang, dan Pippo Belajar Binatang.
Di saat yang sama, Arsanesia berhenti melayani bisnis B2B dan fokus mengembangkan Arsa Kids. Untuk monetisasinya, seluruh mobile game yang dibuat Arsanesia menggunakan in-app purchase. Agar Arsanesia dapat terus mengembangkan produk B2C, sejak pertengahan tahun ini perusahaan mendapat investasi tahap awal dari DNC dengan nominal dirahasiakan. Arsanesia akan menggunakan dana tersebut untuk menemukan produk B2C yang tepat dan bisa menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
“Sebelum DNC masuk, lebih dari 90% [revenue] dari B2B. Kami sekarang sudah tidak lakukan B2B sama sekali, makanya unit B2C harus perform banget. Ini yang menantang karena ibarat kata B2C adalah nature dari perusahaan game.”
Agate Studio
Hampir mirip dengan perjalanan Arsanesia, Agate Studio, perusahaan game yang sama-sama berasal dari Bandung, juga harus menempuh jalur B2B sejak pertama kali dirintis pada 2009.
Agate mulai dirintis ketika 18 orang mahasiswa tingkat tiga di ITB, termasuk Arief Widhiyasa (CEO Agate) dan Aditia Dwiperdana (Serious Games Studio Head Agate) tertarik ikut beberapa kompetisi membuat game di 2008. Meski tidak ada yang dimenangkan, hal itu justru membuat mereka jadi tertarik untuk mengembangkan studio game lokal.
Di tahun yang sama, tim Agate mendapat kesempatan untuk ikut memamerkan game buatannya di Indonesia Game Show Jakarta. Pengunjung booth yang memainkan game Agate ternyata responnya sangat positif, memicu semangat untuk menyeriusi bisnis ini lebih dalam.
“Menurut pengunjung perasaan mereka saat main game sangat senang. Ini jadi titik balik kami bahwa buat game itu bukan untuk menyenangkan diri sendiri saja, tapi bisa buat orang lain ikut bahagia,” kata Aditia.
Alhasil, tim pun mulai meresmikan Agate menjadi studio di April 2009. Awalnya mereka memberikan catatan, apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak menghasilkan penghasilan terpaksa akan ditutup. Rata-rata dari mereka belum mendapat restu orangtua.
Modal mendirikan studio itu berasal dari patungan masing-masing pendiri, total dana yang didapat sekitar Rp120 juta. Agate mulai memproduksi 40 game Flash dan menjualnya ke berbagai portal marketplace, namun hanya 18 di antaranya yang laku.
Salah satu game perdana Agate, English Defendant laku dengan harga US$500, dengan kata lain tidak balik modal. Sampai akhirnya dana operasional habis. Sebab lebih dari separuh modal habis untuk menyewa rumah beserta perabotannya yang memakan biaya sekitar Rp100 juta.
Seluruh founder pun terpaksa harus digaji sebesar Rp50 ribu selama enam bulan dengan waktu kerja hingga 15 jam sehari. Akhirnya Agate memutuskan untuk mendirikan divisi advergame (B2B, B2B2C, dan B2G) demi memutar arus kas.
“Digaji Rp50 ribu itu karena ada dua alasan, kita butuh latihan manajemen untuk beneran gaji tiap bulan. Lagipula kami masih dapat uang saku dan tinggal dengan orang tua. Kedua, karena kita tidak mau jadi software house yang kumpul bila ada proyekan saja. Selama ngerjain proyek itu enggak jelas entitasnya. Kita memang ingin Agate jadi mata pencaharian yang layak.”
Founder baru bisa digaji sesuai standar UMR setahun kemudian, setelah Agate terjun ke advergame. Proyek pertama yang dikerjakan Agate adalah membuat game untuk Microsoft dengan menggunakan teknologi Silverlight. Nilai proyeknya sekitar belasan juta, sayang Aditia enggan membeberkan detilnya.
Sejak terjun ke advergame, Agate mulai bisa membayarkan gaji sesuai UMR. Mulai dapat mengembangkan tim, sebab tujuan Agate didirikan adalah wadah yang menampung talenta dengan kesamaan visi. Orang lokal dapat bekerja di perusahaan game, tanpa harus ke luar negeri dengan standar gaji yang tidak terlalu besar.
“Kita ngejar-nya bukan per orang bisa digaji besar, tapi bisa menampung orang lebih banyak. Sejauh ini bisnis terus berkembang dan total tim ada 120 orang. Itu pun masih kurang karena banyak servis yang akhirnya tidak bisa diambil karena overload.”
Divisi advergame di Agate akhirnya menjadi trademark di benak pemain industri. Puluhan klien sudah ditangani, mulai dari perusahaan agency, EO, FMCG, hingga untuk keperluan kampanye presiden. Nilainya bisa mencapai ratusan juta tergantung kompleksitasnya. Komposisi pendapatan Agate bisa dibilang imbang 50-50 antara advergame dan produk B2C.

Agate terbilang cukup sering mengajukan pinjaman kredit ke bank, namun selalu ditolak karena tidak memiliki aset yang bisa dijadikan agunan. Padahal Agate sudah menyodorkan invoice perjanjian bisnis yang pasti dibayarkan klien.
Aditia mengaku Agate pernah hampir mendapat fasilitas KUR ritel dengan plafon yang dibutuhkan sebesar Rp500 juta, tapi tidak jadi karena prosesnya sudah terlanjur ditutup.
Kendati sudah terjun ke advergame, tidak lantas Agate meninggalkan “khitah”-nya sebagai perusahaan game. Di 2010, Agate tetap memproduksi mobile game dengan memakai metode monetisasi in-app purchase.
Sumber pendanaannya berasal dari subsidi perolehan profit bisnis B2B. Dari seluruh produk B2C yang dirilis Agate, paling tidak semuanya berhasil mencapai Break Even Point (BEP), walaupun belum ada yang benar-benar mencetak profit hingga berkali-kali lipat.
Dalam manajemen pembuatan game, Agate selalu melakukan riset pasar, bagaimana visibilitas dan proyeksi sebelum membuat minimum viable product (MVP). Kemudian versi Beta Plus untuk dievaluasi selama tiga bulan dengan merilis langsung ke pengguna atau negara tertentu demi melihat traksi. Dari situ Agate baru bisa memastikan apakah produk tersebut layak dilanjutkan atau tidak.
“Dulu sih kita idealis, sekarang enggak. Kalau awal idealis tapi dapat dibuktikan lewat validasi bagaimana kenyataan di pasarnya bagaimana, itu bisa. Kita pernah buat game yang selesainya sampai setahun. Jadinya malah backfire, tren sudah terlalu banyak berubah. Sekarang kita mulai gesit untuk develop produk.”
Selain memutar profit sendiri, Agate mendapat tambahan dana segar dari empat angel investor lokal di 2011. Mereka kenal dengan tim Agate secara personal dan percaya dengan apa yang ingin dilakukan. Tahun lalu, Agate mendapat investasi Pra Seri A dari modal ventura lokal Maloekoe Ventures senilai lebih dari Rp13 miliar.
Bila ditotal hingga kini, Agate sudah merilis lebih dari 200 game dan dimainkan oleh lebih dari 5 juta pengguna, baik di Indonesia maupun secara global.
Beberapa mobile game terbaru Agate di antaranya Fantasista, Love Spice, Dungeon Chef, Kuis Iseng, Trio Lestari, dan Juragan Terminal. Sebagian di antaranya khusus dirilis untuk pasar internasional.