Ketika saya masih SMP, saya tertarik dengan sejarah Tiga Kerajaan di Tiongkok karena memainkan game Dynasty Warriors. Saat itu, terbersit sedikit rasa bersalah dalam hati saya karena saya lebih familier dengan tokoh-tokoh di Tiga Kerajaan daripada pahlawan Indonesia. Namun, apa boleh buat, pada tahun 2000-an, tidak ada game yang membahas sejarah Indonesia.
Sekarang, industri game di Indonesia sudah jauh lebih berkembang. Tidak hanya jumlah developer game Indonesia yang bertambah, kualitas game buatan developer lokal juga semakin baik. Dengan begitu, semakin banyak pula game-game yang memiliki unsur khas Indonesia di dalamnya. Salah satunya adalah Tirta dari Agate.
Tirta
Tirta adalah game terbaru yang tengah Agate garap. Game yang diperkirakan akan diluncurkan pada 2022 ini akan fokus pada kebudayaan masyarakat Bali. Dalam game ini, Anda akan bermain sebagai seorang priestess yang harus menjelajah Bali dan pulau-pulau di sekitarnya untuk melakukan ritual. Dalam perjalanannya, dia harus mengatasi berbagai masalah yang mengancam keberadaan makhluk dan binatang mistis yang ada di Bali.
Menggunakan keahlian bela diri dan sihir elemental, para pemain akan diminta untuk mengalahkan beragai monster. Di Tirta, para gamer juga akan menghadapi berbagai puzzle saat mereka menjelajah Bali. IGN menyebutkan, dari segi gameplay, Tirta mengingatkan mereka akan Legend of Zelda: Breath of the Wild. Memang, di Tirta, para pemain juga akan bisa menjelajah Bali untuk mencari tahu tentang lore dalam game.
Namun, tentu saja, Tirta akan tampil beda dari Breath of the Wild. Pasalnya, di Tirta, Agate sengaja untuk menonjolkan unsur budaya Bali. “Tirta membawa tema dan cerita yang unik bagi dunia, yang dirancang berdasarkan legenda Indonesia. Tema ini ditunjukkan salah satunya melalui grafis yang cantik agar menonjolkan karakter dan arsitektur yang terinspirasi budaya lokal,” kata Cipto Adiguna, VP of Consumer Games, Agate.
Lebih lanjut, Cipto menjelaskan, alasan Agate membuat game dengan unsur budaya Indonesia yang sangat kental adalah karena mereka ingin memamerkan kemampuan dan budaya Indonesia di hadapan dunia. “Banyak orang asing yang belum mengenal Indonesia, baik dalam hal budayanya maupun bahwa kita memiliki talenta game development yang kuat. Tirta dibuat dengan impian menancapkan bendera Indonesia dan memperkenalkan kemampuan kita pada dunia,” ujarnya.
Meskipun begitu, Agate juga ingin memastikan bahwa Tirta tetap relevan dengan pasar global. Karena itulah mereka memilih untuk menampilkan budaya Bali, yang memang sudah sangat dikenal di kalangan turis mancanegara. Memang, bagi sebagian orang asing, nama Bali lebih familier daripada Indonesia.

Cipto mengungkap, ide dan konsep untuk Tirta muncul pada akhir 2018. Sementara proses pembuatan teknis dari game tersebut baru dimulai pada awal 2019. Saat ini, ada delapan orang yang sedang mengerjakan Tirta. “Jumlah ini dirasa ideal untuk bergerak cepat dan mencoba banyak ide baru,” ujar Cipto melalui pesan singkat. “Jumlah anggota tim direncanakan bertambah ketika game masuk tahap produksi.”
Keputusan Agate untuk menjadikan budaya Bali sebagai tema utama dari game terbarunya — yang akan tersedia di PC, PlayStation 4 dan 5, serta Nintendo Switch — membuat saya bertanya-tanya…
Perlukah Memasukkan Konten Lokal Dalam Game?
Agate bukan satu-satunya developer Indonesia yang pernah memasukkan unsur kearifan lokal ke dalam game-nya. Ada beberapa developer lain yang juga sukses menyelipkan konten khas Indonesia di game buatan mereka. Salah satunya adalah Digital Happiness. Dengan DreadOut, developer asal Bandung itu sukses membuat game horor dengan cita rasa lokal, menampilkan hantu-hantu khas Indonesia, seperti pocong dan kuntilanak.
Saya lalu menghubungi Rachmad Imron, CEO Digital Happiness, menanyakan tentang alasan mereka untuk menonjolkan konten lokal di DreadOut. Imron menjelaskan, salah satu alasan Digital Happiness adalah karena ketika itu, belum ada game horor yang fokus pada cerita mistis lokal. Jadi, menampilkan konten khas Indonesia justru membuat DreadOut tampil unik.
“Kami pikir, kalau head-to-head perang teknologi dengan developer asing, kita pasti kalah. SDM dan experience juga pasti kalah, karena industri game mereka sudah berkembang selama puluhan tahun,” kata Imron. “Yang bisa kita lakukan ketika itu ya menggunakan tema konten lokal, hantu domestik, yang tidak dikenal oleh para developer asing.” Dengan begitu, para pemain akan bisa merasakan pengalaman bermain game horor yang berbeda dari game horor kebanyakan.
Meskipun konten lokal justru menjadi keunikan DreadOut, Imron percaya, konten lokal tidak seharusnya menjadi prioritas pertama para developer. “Yang paling penting adalah gameplay itu sendiri. Pada akhirnya, pemain tidak peduli ada atau tidaknya konten lokal dalam game. Mereka akan lebih peduli pada gameplay: gampang atau tidak, seru atau tidak,” jelasnya. “Kami selalu mencoba untuk mengedepankan gameplay terlebih dulu. Adapun memasukkan konten lokal, kita akan coba sesubliminal mungkin, bukan hard sell. Bisa dari setting, kostum, dan lain sebagainya. Intinya, mencari sesuatu yang unik, yang tidak sering dipakai oleh media/developer lain.”

Contoh lain game buatan developer Indonesia yang mengandung muatan lokal adalah Coffee Talk. Memang, konten khas Indonesia dalam game tersebut tidak segamblang DreadOut atau Tirta, tapi Coffee Talk tetap menyisipkan konten lokal dalam bentuk resep minuman khas Indonesia.
Mohammad Fahmi, kreator game indie dan yang dulu jadi penulis skenario Coffee Talk punya pendapat yang sama dengan Imron. Perlu atau tidaknya memasukkan konten khas Indonesia ke dalam game tergantung pada game itu sendiri. Dia menjelaskan, jika developer memaksakan untuk memasukkan konten lokal ke dalam game-nya, hal itu justru bisa membuat konten itu terlihat buruk.
“Idealnya sih, kita bisa dan mau mempromosikan sesuatu yang ada dari kita, seperti budaya. Tapi, perlu juga menentukan penempatan yang pas,” kata Fahmi saat dihubungi oleh Hybrid.co.id. “Jangan sampai niatnya mau mempromosikan budaya lokal, tapi malah jadi bumerang dan membuat game-nya jadi kurang dan pesan yang ingin disampaikan justru tidak tersampaikan dengan baik.”
Senada dengan Fahmi, Program Manager, Asosiasi Game Indonesia, Febrianto Nur Anwari mengungkap, perlu atau tidaknya memasukkan konten lokal dalam game tergantung pada target gamer dari sebuah game. “Konten lokal bisa menjadi penting jika diimbangi dengan riset yang mendalam dan dikemas dengan gameplay yang memang disukai oleh target pasarnya,” kata Febri. “Dengan begitu, developer bisa memperkenalkan konten lokal dan para gamer bisa tetap menikmati konten tersebut.”
Tujuan Memasukkan Konten Lokal?
Jika gameplay tetap jadi prioritas pertama bagi developer ketika membuat game, lalu kenapa masih ada developer yang mau memasukkan konten khas Indonesia? Jawaban pertama yang terpikir oleh saya adalah idealisme. Seorang kreator punya hak prerogatif untuk memasukkan idealismenya ke dalam karyanya. Developer bisa saja menyelipkan idealismenya ke dalam game buatannya. Kami pernah membahas masalah game dan idealisme di sini.
Ketika saya menanyakan tentang tujuan developer memasukkan konten lokal dalam game, Imron menjawab, “Hal itu tergantung developer-nya sih. Saya yakin selalu ada developer yang punya idealisme. Namun, semua tetap harus ada pertimbangan ekonomis serta erat dengan strategi marketing-nya.”
Sementara itu, Fachmi mengatakan, developer bisa punya alasan bisnis dan altruistik untuk memasukkan konten lokal dalam game mereka. “Bisa memuaskan idealisme sekaligus menjadikan konten lokal sebagai keunikan game, ini jalur yang indie sekali kan?”

Sayangnya, tidak semua developer punya tujuan yang “murni” ketika mereka memasukkan konten khas Indonesia ke dalam game mereka. Ada juga developer yang memasukkan konten lokal dengan tujuan untuk memenangkan hati gamer Indonesia dengan embel-embel “buatan Indonesia” atau “game khas Indonesia”. Menurut Febri, hal inilah yang bisa menyebabkan masalah. Pasalnya, jika konten lokal dalam game tidak diimbangi dengan gameplay yang menarik serta kualitas yang baik, hal ini justru akan membuat para pemain kecewa, yang bisa berakhir dengan kehilangan kepercayaan pada developer.
“Biasanya, game yang dibuat hanya karena ‘local pride‘, risetnya kurang mendalam. Dan usianya tidak bertahan lama. Karena, orang-orang tertarik untuk download hanya karena ada bau-bau Indonesia-nya. Ketika mereka memainkan game itu dan ternyata kurang oke, akhirnya mereka justru uninstall,” jelas Febri. Meskipun begitu, tetap ada developer yang mengelu-elukan konten lokal demi memasarkan game mereka. Menurut Febri, hal ini terjadi karena memang masih ada gamer Indonesia yang merasa “bangga” dengan game khas Indonesia. Developer akan bisa dengan mudah memenangkan hati para gamer tersebut selama mereka membuat game dengan unsur khas Indonesia.
“Setahu saya, di forum-forum gamer, masih banyak gamer yang merasa ‘bangga’ dengan game bernuansa Indonesia. Mereka berbagi informasi di grup dan kadang-kadang, mereka menambahkan, ‘Kalau membajak game, game internasional saja, jangan game Indonesia. Game Indonesia harus di-support dengan dibeli atau di-download‘,” ungkap Febri. “Yang membuat game seperti itu (game yang menjual dengan embel-embel “khas Indonesia” — red) biasanya developer-developer baru, yang bisa saja baru pertama kali rilis game, yang ingin berkontribusi mengenalkan budaya Indonesia ke para gamer, walau mereka tidak yakin dengan kualitas game buatan mereka. Tujuannya ya agar game mereka lebih cepat dikenal dan mudah masuk ke komunitas gamer-gamer yang saya sebutkan tadi.”
Konten Lokal di Game untuk Audiens Global, Menjual?
Apapun alasannya, memasukkan konten khas Indonesia ke game memang tidak salah. Namun, pada akhirnya, developer game adalah perusahaan yang punya tujuan untuk mendapatkan untung. Untuk itu, developer bisa saja menyasar pasar global dan tidak sekedar pasar Indonesia saja. Hanya saja, mungkinkah developer menyasar pasar global jika mereka memasukkan konten khas Indonesia ke dalam game mereka? Jawaban singkatnya: ya.
“Dengan asumsi target pasar internasional, konten lokal itu bisa memberikan ‘warna’ tersendiri ke karya kita, sesuatu yang buat game kita berbeda dari ribuan game lain yang rata-rata dikembangkan di Amerika Utara, Eropa, atau Asia Timur,” ungkap Fachmi.
Imron juga punya pendapat yang sama dengan Fachmi. Namun, dia mengingatkan, keberadaan konten lokal dalam sebuah game bukanlah jaminan bahwa game tersebut akan laku di pasar global. “Karena ada banyak faktor di formula laku atau tidaknya game di pasar,” ujarnya.
Memasukkan konten “lokal” dari negara-negara tertentu merupakan salah satu strategi developer untuk memenangkan hati para pemain di negara atau kawasan tertentu. Imron memberikan contoh karakter Gatot Kaca dan Nyi Roro Kidul di Mobile Legends atau Gajah Mada dan Tribuana Tungga Dewa di Civilization V. Dalam setiap game Assassin’s Creed pun, Ubisoft biasanya fokus pada satu negara. “Hal ini menunjukkan bahwa developer asing pun menggunakan strategi pelokalan game untuk menggaet pasar-pasar domestik,” ungkapnya.
Satu hal yang harus diingat, ujar Imron, developer harus tetap mengutamakan gameplay. Tujuannya, agar game yang mereka buat tetap relevan dengan audiens global walau game itu mengandung konten lokal dari negara-negara tertentu. “Gameplay first, konten lokal bisa dipikirkan belakangan. Kalaupun bisa, itu akan jadi value lebih bagi pemain,” katanya. “Hal ini juga bisa dilihat dari seri The Witcher, yang menampilkan budaya Polandia, tapi hanya sebagai background dari game itu sendiri. Sementara pada game The Witcher, tidak ada embel-embel ‘based on Poland myth‘.”

Baik Tirta maupun DreadOut menjadikan konten lokal sebagai ujung tombak, sesuatu yang membuat kedua game itu unik. Namun, sebenarnya, konten lokal dalam game juga bisa disisipkan dalam hal-hal kecil. Misalnya, di Coffee Talk, Toge Productions memasukkan unsur lokal dengan menyelipkan resep minuman khas Indonesia. Mengingat Coffee Talk bercerita tentang barista, maka konten lokal tersebut akan terasa natural.
Febri memuji cara Toge Productions untuk menyelipkan konten lokal dalam Coffee Talk. “Coffee Talk itu punya setting di dunia fantasi kan, ada elf-nya juga. Tapi, ketika sedang main, pemain tiba-tiba menemukan resep kopi lokal. Mereka jadi surprised dan hal ini justru memberikan impresi yang bagus,” ungkap Febri. Dia bercerita, ada orang asing yang mengaku mencoba untuk membuat kopi jahe karena menemukan resep minuman tersebut dalam Coffee Talk. Hal ini menjadi bukti bahwa Coffee Talk telah sukses untuk memperkenalkan bagian dari Indonesia — dalam hal ini minuman — ke audiens global.
Selain makanan dan minuman, ada banyak cara lain bagi developer untuk menyelipkan konten lokal dalam game mereka. Fachmi menjelaskan, konten khas Indonesia yang bisa dimasukkan dalam game bisa berupa item, senjata, dongeng, musik, tarian, atau bahkan arsitektur. Yang paling penting, dia menegaskan, adalah untuk memastikan konten lokal itu sesuai dengan tema dari game yang sedang dibuat.
“Di game-ku berikutnya, What Comes After, kan setting-nya di kereta, yang sebenarnya KRL, karena cerita ini terinspirasi dari mas-mas yang ketiduran di KRL,” ujar Fachmi. “Tapi, semua kereta lokal itu kan terlihat mirip. Jadi, game ini bisa diinterpretasikan secara bebas mengambil setting lokasi dimana. Karena itu, aku menjual konten Indonesia dalam bentuk lain, yaitu musik.” Dia bercerita, dia menggunakan lagu berbahasa Indonesia dari band Indonesia sebagai musik di trailer dan ending song dari game What Comes After.
Sisi Gelap Game dengan Konten Lokal
Konten lokal bisa membuat sebuah game tampil unik. Namun, seperti yang disebutkan oleh Imron, keberadaan konten lokal bukan jaminan sebuah game akan sukses. Dan memang, tidak semua game dengan konten lokal sukses di pasar. Ada juga game-game yang mengusung kearifan lokal tapi berakhir dengan ketidakpastiaan waktu peluncuran.
Salah satu contohnya adalah Boma Naraka Sura. Developer dari game ini mencari pendanaan untuk membuat game tersebut melalui Kickstarter. Proyek Boma Naraka Sura diluncurkan di Kickstarter pada Juli 2015. Satu bulan kemudian, mereka berhasil memenuhi target pendanaan. Secara total, mendapatkan US$28 ribu dari 625 pendukung. Sayangnya, ketika kami mencoba mencari berita tentang peluncuran game tersebut, kami tidak dapat menemukannya.
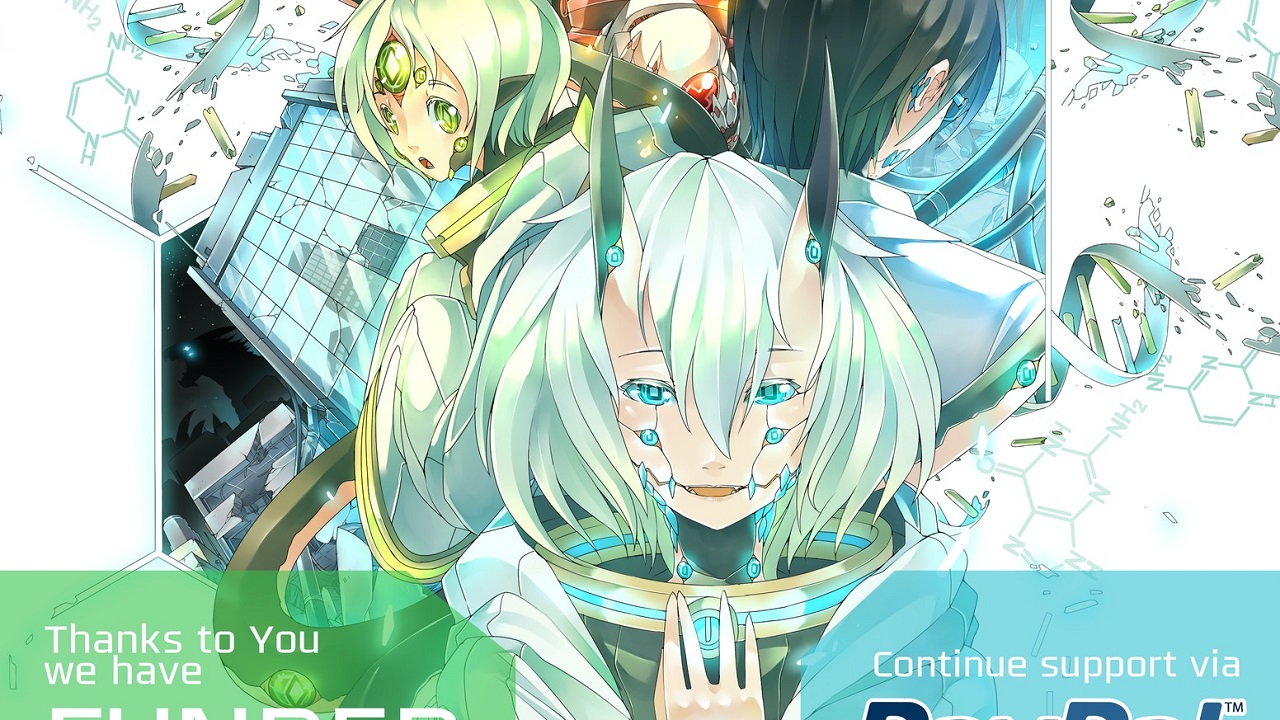
Contoh lainnya adalah Pale Blue. Sama seperti Boma Naraka Sura, pendanaan untuk pengembangan game 2D platformer itu dikumpulkan melalui Kickstarter. Proyek untuk mengumpulkan dana pengembangan dari Pale Blue diluncurkan di Kickstarter pada Mei 2014. Pada awalnya, target pendanaan yang ditetapkan oleh developer Pale Blue, Tinker Games, adalah US$48 ribu. Pada akhirnya, mereka berhasil mendapatkan US$59,5 ribu. Namun, pada akhirnya, Tinker Games hanya dapat meluncurkan demo dari game tersebut.
Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan, kami menemukan bahwa alasan Pale Blue tak pernah diluncurkan adalah karena Tinker Games telah kehabisan dana sebelum game selesai dibuat. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak memiliki orang yang bertanggung jawab untuk mengatur alur kerja tim, seperti produser, seperti dikutip dari Duniaku. Tak hanya itu, mereka juga tidak punya orang yang mengatur pengeluaran selama proses pengembangan. Hal ini membuat tim developer bekerja tanpa arah. Pada akhirnya, target yang telah ditetapkan oleh tim developer tidak tercapai.
Baik Pale Blue maupun Boma Naraka Sura merupakan game buatan developer lokal yang mencari pendanaan di Kickstarter. Keduanya juga berhasil mencapai target pendanaan. Hal ini menunjukkan bahwa game buatan developer Indonesia — dan mengandung unsur budaya dari Asia Tenggara dalam kasus Boma Naraka Sura — diminati jika dikemas dengan baik. Sayangnya, kedua game itu tak pernah dirilis ke pasar. Dalam kasus Pale Blue, hal ini terjadi karena keteledoran developer dalam manajemen proyek.
Kesimpulan
Dari sini, saya menyimpulkan, kesuksesan sebuah game tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya konten lokal dalam game tersebut. Kualitas game tetap menjadi tolok ukur nomor satu. Konten lokal hanyalah “vitamin tambahan”, menurut Fachmi. Sementara Febri menekankan pentingnya manajemen proyek bagi developer dalam mengembangkan game. Karena, jika tidak hati-hati, developer bisa kehabisan dana sebelum proses pengembangan selesai.
“Seperti mobil yang kehabisan bensin di tengah jalan,” ujar Febri.




















